Kepercayaan Publik Dan Politik Uang
This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA
Overview
Download & View Kepercayaan Publik Dan Politik Uang as PDF for free.
More details
- Words: 953
- Pages: 2
Kepercayaan Publik Dan Politik Uang Oleh : Muhammad Sholeh*
Seseorang mengirimkan pesan pendek ke rubrik SMS di sebuah koran ini beberapa waktu lalu. Ia menganalogkan berbagai terminologi Pemilu dengan dunia pertanian. Dapil digambarkan sebagai ladang, konstituen sebagai tanaman dan tim sukses sebagai pupuknya. Sedikit mengejutkan, ia juga menganalogkan bagi-bagi uang sebagai werengnya (hama pertanian). Tidak diketahui motif dari analog yang dipesankan pengirim SMS tersebut. Bisa jadi analog itu muncul gara-gara ia sendiri adalah seorang Caleg yang tidak berdaya berhadapan dengan kuatnya dominasi modal dalam Pemilu 2009 ini -sebuah ekspresi keputusasaan. Atau boleh jadi SMS itu adalah suara lirih yang dibisikkan oleh seseorang yang sedang 'prihatin' menyaksikan pemilih dan Caleg yang cenderung transaksional. Wallahu a'lamu bisshowab. Pesan yang hampir sama ditulis oleh seorang Caleg DPRD tingakat II di Jawa Tengah pada halaman web blognya. Menurutnya, politik uang sama dengan menabur benih korupsi. Uang yang keluar dari kantong para Caleg dan diterima para pemilihnya, kemudian hari akan diambil dari keringat rakyat dan kembali masuk ke kantongnya. Semakin besar yang dikeluarkan dari kantong, semakin besar uang rakyat yang nantinya akan masuk ke kantong. Siapapun penulisnya dan apapun yang melatarbelakanginya, dua pesan tersebut cukup menarik perhatian. Caleg atau bukan si penulisnya, pesan tersebut adalah sebuah jeritan yang ingin menegaskan pertanian tidak akan baik hasilnya bila diserang hama. Pesan itu mendeklarasikan bahwa proses politik tidak akan menghasilkan out put yang diharapkan bila terus dibayangi dengan praktek uang. Menarik karena pesan tersebut cukup paradok bila dihadapkan pada realita di lapangan. Satu sisi, pesan itu menggambarkan adanya sebuah kesadaran yang jernih bahwa proses politik harus bisa menghasilkan out put yang diharapkan. Sementara pada sisi lain, realitas di lapangan menunjukkan praktek-praktek politik uang masih terus berlanjut. Dua hal yang saling bertentangan. Ada apa sebenarnya dengan dunia perpolitikan kita? Regulasi dan perundangan yang menjadi rule of the game bagi pertarungan politik sudah semakin baik. Meski ada beberapa yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), UU 10 tahun 2008 tentang Pemilu dipandang jauh lebih memenuhi unsur keadilan bila dibanding dengan UU sebelumnya. Ada apa sebenarnya? Diskusi dengan beberapa teman aktifis LSM, terlontar sebuah jawaban. Munculnya praktek uang lebih karena keputusasaan pemilih terhadap kinerja Parpol dan pemerintahan yang terbentuk. Masyarakat sudah jenuh dengan janji-janji dan gagasan perjuangan yang hanya manis di bibir. Kalau sebelumnya rakyat 'dipermainkan' oleh para politisi busuk, jangan salahkan bila sekarang ganti rakyat yang mempermainkan mereka. Diskusi dengan beberapa teman aktifis Parpol, terlontar sebuah jawaban. Politik uang terpaksa harus dilakukan karena masyarakat pemilih sekarang berubah menjadi sangat pragmatis. Untuk mewujudkan idealisme dan perjuangan, politisi harus memenangi pertarungan politik dan bisa menarik simpati pemilih. Jangan salahkan bila para politisi menjadi busuk, semua itu garagara menuruti kemauan dan keinginan para pemilih busuk. Tidak ada jawaban dan sekaligus solusi penyelesaiannya. Baik pemilih maupun yang dipilih sama-sama 'terpaksa'. Sama-sama tidak merasa bersalah. Menthok. Kedua pihak memiliki nalar yang cukup beralasan. Permasalahan menjadi persis dengan menjawab pertanyaan; dulu mana ayam atau telor. Namun demikian, ada satu hal yang bisa ditemukan pada masing-masing pihak. Baik pemilih maupun politisi sudah sama-sama kehilangan kepercayaan antara satu dengan yang lain. Pemilih tidak percaya, setelah memilih nanti aspirasi dan hak-haknya akan benar-benar diperjuangkan. Demikian juga politisi. Ia tidak begitu saja percaya pemilih akan memilihnya bila tidak diberi kompensasi uang. Demi cita-cita luhur, 'pengorbanan' dalam bentuk uang harus dilakukan. Faktor kepercayaan (trust) menjadi sangat penting dalam kontek ketidakharmonisan interaksi antara pemilih dan politisi. Interaksi kedua pihak bisa berjalan baik bila keduanya saling bisa dipercaya dan mempercayai. Oleh karena itu, kepercayaan menjadi kunci utama atas out put proses politik yang sesuai dengan harapan, sekaligus tergesernya praktek politik uang. Daya pilih (elektibilitas) seorang kandidat memang tidak seratus persen ditentukan oleh kepercayaan pemilih. Bisa saja ia terpilih lebih karena tebar pesona dan pencitraan yang tepat. Tapi, bila hal demikian berlangsung secara terus menerus, pemilih pasti akan belajar dari
pengalamannya. Dan yang pasti, kepercayaan akan menipis serta ikatan psikopolitis antara pemilih dengan politisi akan memudar. Situasi demikian sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia. Di Amerika dan Eropa, situasi yang sama juga pernah dialami oleh pemilih dan lembaga-lebaga politik di sana. Seperti dirilis dalam laporan berkala Friedrich-Naumann-Stiftung (FNC), warga Amerika pernah mengalami 'frustasi politik' yang luar biasa akibat rendahnya kepedulian partai terhadap kesejahteraan masyarakat. Kurang lebih sama juga terjadi di Eropa Barat. Partai dan lembaga politik lainnya kembali mendapat kepercayaan dari warga setelah berhasil merubah diri dengan memberikan pelayanan yang semestinya. Sebelumnya, lembaga-lebaga politik dituding hanya mementingkan lembaganya sendiri tanpa peduli dengan masalah-masalah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat umum. Oleh karena itu, agar segera keluar dari paradok 'telor dan ayam', cukup beralasan bila rasa saling percaya harus secepat mungkin dibangun secara bersama-sama. Momentum Pemilu 2009 menjadi sangat penting bagi catatan perjalan politik kita. Keputusan MK pada UU 10/2008 soal suara terbanyak yang dinilai cukup memenuhi rasa keadilan, tidak boleh menjadikan para Caleg dan pemilih justru melanggar norma-norma keadilan, termasuk diantaranya, politik uang. Politik uang adalah salah satu perilaku yang keluar dari norma keadilan. Politik uang yang dalam terminologi fiqh siyasi disebut sebagai 'siyasaturrisywah' (suap politik) mampu merubah segalanya. Seperti ditulis oleh DR. Adil Al Muthayyirat dalam artikelnya, Al Risywah, suap diharamkan oleh agama karena bisa merubah yang salah menjadi benar, sesuatu yang hina menjadi terhormat dan yang berhak menjadi tidak berhak. Daya ingat pemilih harus diperkuat. Menerima uang dari politisi sama dengan menerima tiket untuk bisa menyaksikan adegan penjarahan uang rakyat. Politisi tidak boleh melupakan, cita-cita luhur dan idealismenya tidak akan tercapai dengan memberi uang kepada pemilih. Kelak, ia hanya akan sibuk mengembalikan modalnya. Sebagai bahan renungan dan peringatan bersama, pantas untuk menyebutkan penafsiran Gus Dur terhadap Al Qur'an Surat Attakatsur. Ayat (1) yang berbunyi 'Alhakum Attakatsur' yang biasa diartikan bermegah-megahan telah melalaikanmu, oleh Gus Dur juga dimaknai dengan persaingan memperebutkan suara dukungan politik telah melalaikanmu. Na'udzubillahi min dzalik. * Penulis adalah Sekretaris DKC Garda Bangsa Kabupaten Jombang
Seseorang mengirimkan pesan pendek ke rubrik SMS di sebuah koran ini beberapa waktu lalu. Ia menganalogkan berbagai terminologi Pemilu dengan dunia pertanian. Dapil digambarkan sebagai ladang, konstituen sebagai tanaman dan tim sukses sebagai pupuknya. Sedikit mengejutkan, ia juga menganalogkan bagi-bagi uang sebagai werengnya (hama pertanian). Tidak diketahui motif dari analog yang dipesankan pengirim SMS tersebut. Bisa jadi analog itu muncul gara-gara ia sendiri adalah seorang Caleg yang tidak berdaya berhadapan dengan kuatnya dominasi modal dalam Pemilu 2009 ini -sebuah ekspresi keputusasaan. Atau boleh jadi SMS itu adalah suara lirih yang dibisikkan oleh seseorang yang sedang 'prihatin' menyaksikan pemilih dan Caleg yang cenderung transaksional. Wallahu a'lamu bisshowab. Pesan yang hampir sama ditulis oleh seorang Caleg DPRD tingakat II di Jawa Tengah pada halaman web blognya. Menurutnya, politik uang sama dengan menabur benih korupsi. Uang yang keluar dari kantong para Caleg dan diterima para pemilihnya, kemudian hari akan diambil dari keringat rakyat dan kembali masuk ke kantongnya. Semakin besar yang dikeluarkan dari kantong, semakin besar uang rakyat yang nantinya akan masuk ke kantong. Siapapun penulisnya dan apapun yang melatarbelakanginya, dua pesan tersebut cukup menarik perhatian. Caleg atau bukan si penulisnya, pesan tersebut adalah sebuah jeritan yang ingin menegaskan pertanian tidak akan baik hasilnya bila diserang hama. Pesan itu mendeklarasikan bahwa proses politik tidak akan menghasilkan out put yang diharapkan bila terus dibayangi dengan praktek uang. Menarik karena pesan tersebut cukup paradok bila dihadapkan pada realita di lapangan. Satu sisi, pesan itu menggambarkan adanya sebuah kesadaran yang jernih bahwa proses politik harus bisa menghasilkan out put yang diharapkan. Sementara pada sisi lain, realitas di lapangan menunjukkan praktek-praktek politik uang masih terus berlanjut. Dua hal yang saling bertentangan. Ada apa sebenarnya dengan dunia perpolitikan kita? Regulasi dan perundangan yang menjadi rule of the game bagi pertarungan politik sudah semakin baik. Meski ada beberapa yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), UU 10 tahun 2008 tentang Pemilu dipandang jauh lebih memenuhi unsur keadilan bila dibanding dengan UU sebelumnya. Ada apa sebenarnya? Diskusi dengan beberapa teman aktifis LSM, terlontar sebuah jawaban. Munculnya praktek uang lebih karena keputusasaan pemilih terhadap kinerja Parpol dan pemerintahan yang terbentuk. Masyarakat sudah jenuh dengan janji-janji dan gagasan perjuangan yang hanya manis di bibir. Kalau sebelumnya rakyat 'dipermainkan' oleh para politisi busuk, jangan salahkan bila sekarang ganti rakyat yang mempermainkan mereka. Diskusi dengan beberapa teman aktifis Parpol, terlontar sebuah jawaban. Politik uang terpaksa harus dilakukan karena masyarakat pemilih sekarang berubah menjadi sangat pragmatis. Untuk mewujudkan idealisme dan perjuangan, politisi harus memenangi pertarungan politik dan bisa menarik simpati pemilih. Jangan salahkan bila para politisi menjadi busuk, semua itu garagara menuruti kemauan dan keinginan para pemilih busuk. Tidak ada jawaban dan sekaligus solusi penyelesaiannya. Baik pemilih maupun yang dipilih sama-sama 'terpaksa'. Sama-sama tidak merasa bersalah. Menthok. Kedua pihak memiliki nalar yang cukup beralasan. Permasalahan menjadi persis dengan menjawab pertanyaan; dulu mana ayam atau telor. Namun demikian, ada satu hal yang bisa ditemukan pada masing-masing pihak. Baik pemilih maupun politisi sudah sama-sama kehilangan kepercayaan antara satu dengan yang lain. Pemilih tidak percaya, setelah memilih nanti aspirasi dan hak-haknya akan benar-benar diperjuangkan. Demikian juga politisi. Ia tidak begitu saja percaya pemilih akan memilihnya bila tidak diberi kompensasi uang. Demi cita-cita luhur, 'pengorbanan' dalam bentuk uang harus dilakukan. Faktor kepercayaan (trust) menjadi sangat penting dalam kontek ketidakharmonisan interaksi antara pemilih dan politisi. Interaksi kedua pihak bisa berjalan baik bila keduanya saling bisa dipercaya dan mempercayai. Oleh karena itu, kepercayaan menjadi kunci utama atas out put proses politik yang sesuai dengan harapan, sekaligus tergesernya praktek politik uang. Daya pilih (elektibilitas) seorang kandidat memang tidak seratus persen ditentukan oleh kepercayaan pemilih. Bisa saja ia terpilih lebih karena tebar pesona dan pencitraan yang tepat. Tapi, bila hal demikian berlangsung secara terus menerus, pemilih pasti akan belajar dari
pengalamannya. Dan yang pasti, kepercayaan akan menipis serta ikatan psikopolitis antara pemilih dengan politisi akan memudar. Situasi demikian sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia. Di Amerika dan Eropa, situasi yang sama juga pernah dialami oleh pemilih dan lembaga-lebaga politik di sana. Seperti dirilis dalam laporan berkala Friedrich-Naumann-Stiftung (FNC), warga Amerika pernah mengalami 'frustasi politik' yang luar biasa akibat rendahnya kepedulian partai terhadap kesejahteraan masyarakat. Kurang lebih sama juga terjadi di Eropa Barat. Partai dan lembaga politik lainnya kembali mendapat kepercayaan dari warga setelah berhasil merubah diri dengan memberikan pelayanan yang semestinya. Sebelumnya, lembaga-lebaga politik dituding hanya mementingkan lembaganya sendiri tanpa peduli dengan masalah-masalah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat umum. Oleh karena itu, agar segera keluar dari paradok 'telor dan ayam', cukup beralasan bila rasa saling percaya harus secepat mungkin dibangun secara bersama-sama. Momentum Pemilu 2009 menjadi sangat penting bagi catatan perjalan politik kita. Keputusan MK pada UU 10/2008 soal suara terbanyak yang dinilai cukup memenuhi rasa keadilan, tidak boleh menjadikan para Caleg dan pemilih justru melanggar norma-norma keadilan, termasuk diantaranya, politik uang. Politik uang adalah salah satu perilaku yang keluar dari norma keadilan. Politik uang yang dalam terminologi fiqh siyasi disebut sebagai 'siyasaturrisywah' (suap politik) mampu merubah segalanya. Seperti ditulis oleh DR. Adil Al Muthayyirat dalam artikelnya, Al Risywah, suap diharamkan oleh agama karena bisa merubah yang salah menjadi benar, sesuatu yang hina menjadi terhormat dan yang berhak menjadi tidak berhak. Daya ingat pemilih harus diperkuat. Menerima uang dari politisi sama dengan menerima tiket untuk bisa menyaksikan adegan penjarahan uang rakyat. Politisi tidak boleh melupakan, cita-cita luhur dan idealismenya tidak akan tercapai dengan memberi uang kepada pemilih. Kelak, ia hanya akan sibuk mengembalikan modalnya. Sebagai bahan renungan dan peringatan bersama, pantas untuk menyebutkan penafsiran Gus Dur terhadap Al Qur'an Surat Attakatsur. Ayat (1) yang berbunyi 'Alhakum Attakatsur' yang biasa diartikan bermegah-megahan telah melalaikanmu, oleh Gus Dur juga dimaknai dengan persaingan memperebutkan suara dukungan politik telah melalaikanmu. Na'udzubillahi min dzalik. * Penulis adalah Sekretaris DKC Garda Bangsa Kabupaten Jombang
Related Documents

Kepercayaan Publik Dan Politik Uang
April 2020 18
Politik Uang Sebagai Pemberontakan Rakyat
April 2020 10
Kepercayaan
May 2020 26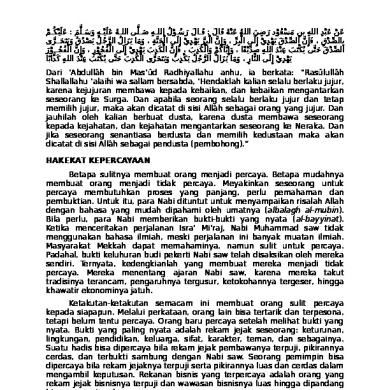
Kepercayaan Dan Kejujuran.docx
November 2019 30
Uang Dan Rejeki
April 2020 19